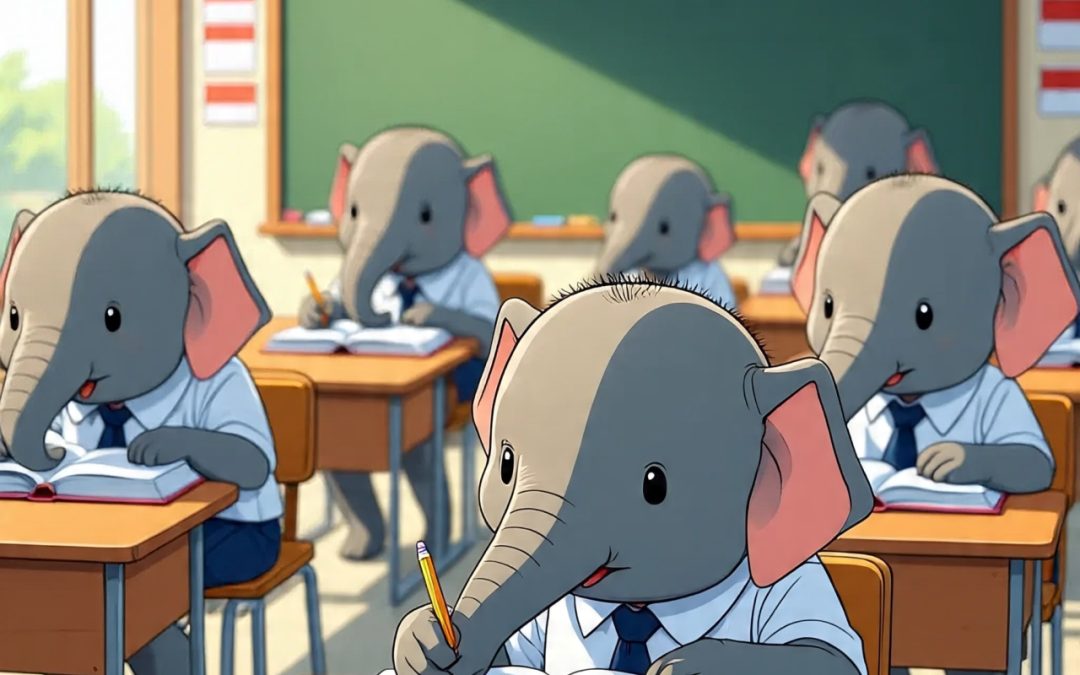Titik Temu Smamsatu | Oleh: M. Islahuddin (Guru Pendidikan ISMUBA Smamsatu Gresik)
Sekolah Gajah: Refleksi Diri dan Kondisi Pendidikan Kita
Kisah tentang Sekolah yang Aneh
Pada suatu masa, di bawah langit yang sama namun dalam iklim politik yang lain, kita pernah mengenal sebuah institusi yang terdengar ganjil: Sekolah Gajah. Letaknya di Way Kambas, Lampung, dan dibangun oleh pemerintah daerah pada zaman Orde Baru. Nama itu sendiri mengandung ironi sebuah sekolah untuk binatang yang tidak pernah mendaftar menjadi murid.
Alasan pendiriannya sederhana, atau setidaknya tampak demikian di mata pejabat: gajah-gajah itu dianggap terlalu “liar”. Mereka merambah ladang, memporak-porandakan tanaman, dan mengganggu stabilitas desa. Dalam bahasa penguasa masa itu, mereka adalah ancaman bagi ketenteraman. Dan “ketenteraman” di era Orde Baru adalah istilah politis: wajah permukaan dari sebuah tatanan yang hendak dikontrol sepenuhnya.
Maka gajah-gajah itu harus dididik atau lebih tepatnya, dijinakkan. Mereka dimasukkan dalam kurikulum tunduk: dilatih menarik kayu, menuruti komando pawang, atau tampil dalam atraksi wisata. Pendidikan di situ bukanlah proses merawat tumbuh, melainkan proyek penjinakan. Gajah yang lahir untuk rimba, dipaksa menjadi tenaga kerja atau tontonan.
Metafora yang Menohok
Kisah itu sekilas terdengar jauh. Tetapi jika kita bercermin, bukankah sekolah-sekolah kita hari ini pun sering berperan seperti Sekolah Gajah?
Anak-anak datang dengan naluri bertanya, imajinasi liar, dan semangat menjelajah. Tetapi begitu memasuki gerbang sekolah, mereka ditertibkan, dipaksa duduk tenang, menyalin, menghafal, dan mengikuti aturan yang seragam. Mereka dianggap terlalu “liar” untuk dibiarkan menjadi dirinya sendiri.
Padahal, setiap anak adalah semesta. Mereka punya benih unik yang tidak bisa dipaksa tumbuh dengan pola sama. Tetapi sistem pendidikan kita dari kebijakan kurikulum, metode mengajar, hingga cara kita menilai berangkat dari logika pengendalian: bagaimana membuat anak-anak patuh dan seragam. Seakan-akan manusia yang beragam harus dipangkas agar muat dalam satu wadah standar.
Kita mungkin lupa bahwa seragam pada dasarnya lahir dari rasa takut. Kita takut jika anak-anak menjadi terlalu liar, lalu mengganggu “ketenteraman” kita. Maka mereka diikat, dijinakkan, diawasi, dipagari angka-angka. Persis seperti gajah yang diikat kakinya sejak kecil: bahkan ketika sudah dewasa, ia tetap percaya dirinya tidak bisa lepas dari tali itu.
Pendidikan: Membebaskan atau Menjinakkan?
Pertanyaan ini sesungguhnya bukan baru. Ki Hadjar Dewantara sudah lama mengingatkan: pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kata kuncinya adalah menuntun, bukan menjinakkan.
Paulo Freire pun menegaskan, pendidikan harus menjadi ruang pembebasan, bukan penindasan yang membungkam. Tetapi dalam kenyataan, berapa banyak ruang kelas kita yang masih membuat anak-anak merasa terpenjara? Berapa banyak guru yang masih mengajar dengan logika “isi botol kosong”, seolah-olah anak tidak punya dunia dalam dirinya?
Kita boleh berbicara tentang digitalisasi, kurikulum merdeka, atau metode mutakhir. Tetapi selama logika dasarnya tetap penjinakan, selama anak masih dilihat sebagai ancaman ketenteraman, maka sekolah kita hanya berganti kulit tetapi tetaplah Sekolah Gajah.
Bayang-Bayang Orde Baru dalam Pendidikan Hari Ini
Warisan Orde Baru tidak hanya pada aspek politik, melainkan juga pada imajinasi pendidikan: keteraturan, stabilitas, ketertiban. Itulah yang diam-diam masih membayangi ruang kelas. Kita lebih takut pada kekacauan daripada rindu pada pertumbuhan. Kita lebih ingin anak-anak duduk diam, daripada mendengar mereka bertanya dengan kritis.
Padahal dunia sedang berubah. Lingkungan rusak, ketidakadilan sosial makin nyata, teknologi melesat tanpa arah. Apakah kita masih akan menjinakkan anak-anak agar sekadar menjadi roda mesin, atau justru membiarkan mereka tumbuh sebagai manusia yang berani merawat bumi, menegakkan keadilan, dan menemukan jalannya sendiri?
Ngudar Rasa: Sebuah Penutup
Mungkin di titik ini, kita perlu berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menengok ke dalam. Kita ini siapa? guru, orang tua, pejabat, atau sekadar orang dewasa yang kebetulan hadir di sekitar anak-anak? Apa yang sebenarnya kita inginkan dari mereka?
Saya sering membayangkan, bagaimana jika suatu hari anak-anak kita menatap kita dengan mata jernih dan bertanya: “Mengapa engkau mengikat kakiku, padahal aku ingin berlari?” Apa jawaban kita?
Gajah-gajah itu dulu dijinakkan agar tidak mengganggu ladang. Tetapi anak-anak kita apakah kita juga ingin menjinakkan mereka agar tidak mengganggu “ketenteraman” kita? Jangan-jangan, justru keberanian mereka untuk berbeda, untuk bertanya, untuk melawan arus, itulah yang akan menyelamatkan masa depan kita bersama.
Pada akhirnya, sekolah bisa menjadi kandang, bisa juga menjadi rimba. Semuanya bergantung pada cara kita memandang anak-anak: sebagai makhluk yang perlu dikendalikan, atau sebagai jiwa yang layak diberi ruang tumbuh.
Dan mungkin, di tengah hening senja, kita hanya perlu berani berkata dalam hati: sudah cukup kita menjinakkan. Kini saatnya kita menemani.