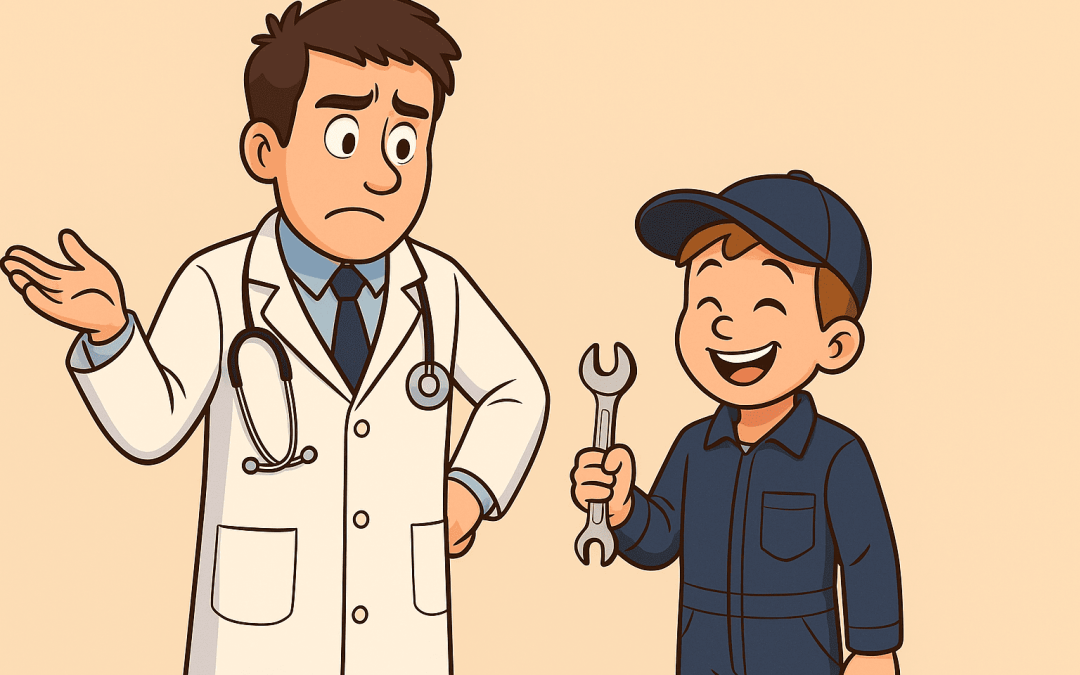Titik Temu Smamsatu | Oleh: M. Islahuddin (Guru Pendidikan ISMUBA Smamsatu Gresik)
“Anakku itu nggak boleh main gadget, bahaya!” ujar seorang teman dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, ada pula yang dengan nada mantap berkata, “Justru sejak kecil harus dikenalkan teknologi, biar nggak ketinggalan.”
Percakapan semacam ini bukan sekali dua kali saya dengar. Dari arisan keluarga, obrolan WhatsApp grup wali murid, hingga diskusi santai di teras rumah tetangga tema parenting selalu hangat dibicarakan. Semua punya resep jitu masing-masing, dan menariknya, semua disampaikan seolah tanpa celah kesalahan. Dalam urusan anak, hampir setiap orang merasa paling benar.
Sejak menjadi orangtua, saya pun sering terjebak dalam keyakinan serupa. Mengasuh, mendidik, menanamkan nilai, mendisiplinkan, hingga menjaga kesehatan anak seakan menjadi ladang pembuktian kebenaran mutlak. Padahal, anak bukanlah proyek ambisi, melainkan manusia yang punya hak untuk tumbuh dengan jalannya sendiri.
Jika dalam politik orang bisa merasa 99 persen benar, maka dalam urusan parenting keyakinannya bisa tembus 100 persen. Ironisnya, justru di situlah persoalannya: kita terlalu yakin bahwa cara kitalah yang paling tepat.
Entah itu ‘akibat’ atau ‘sebab’ dari munculnya beragam komunitas dan grup parenting, baik di media sosial maupun yang berlanjut ke pertemuan darat dengan beragam nama.
Saya sendiri bukan penggemar grup parenting, karena jika semua saya ikuti, saya bisa berada dalam banyak grup saat anak mulai masuk sekolah. Namun menyimak informasi yang beredar ringan lewat sharing info di timeline sosmed selalu menjadi renungan gaduh dalam benak saya tentang: Bagaimana menjadi orangtua yang baik?
Beberapa orangtua berpendapat bahwa parenting yang baik adalah dengan menerapkan disiplin tinggi dan pembekalan beragam skill yang mumpuni.
Orangtua bergenre ini akan membanjiri sekolah-sekolah terbaik yang ada di kota. Mulai dari sekolah dwi bahasa (bahkan tri bahasa) hingga sekolah dengan beragam ekstrakulikuler sampai dengan asrama dan fasilitas yang keren. Berapapun ‘tarif’ yang dipatok tidak jadi kendala. Yang penting anak-anak ‘tercetak’ dengan displin tinggi dan tumbuh dengan beragam skill.
Anak Bukan Proyek
Di banyak keluarga, anak sering diperlakukan layaknya “proyek prestasi”. Ia harus bersekolah di lembaga favorit, meraih ranking tinggi, memenangkan lomba, bahkan diarahkan untuk memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan keinginan orangtua. Semua langkah seolah sudah digariskan.
Cinta, dalam kasus ini, berubah menjadi kendali. Anak diatur jam tidurnya, dipilihkan sekolahnya, bahkan ditentukan siapa yang pantas jadi temannya. Semua itu dibungkus dalam dalih kasih sayang. Padahal, cinta yang mengekang sering kali menjelma belenggu.
Psikologi perkembangan mengenalkan konsep autonomy support: memberi ruang kebebasan agar anak belajar mengambil keputusan, sekaligus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Anak perlu kesempatan untuk gagal, untuk jatuh, lalu bangkit dengan caranya sendiri.
Proses inilah yang menumbuhkan kemandirian dan daya tahan hidup.
Sayangnya, ruang semacam ini sering kali sempit. Kita terlalu takut anak “keliru”, sehingga kita sendiri yang sibuk menentukan semua langkahnya.
Orangtua Juga Murid
Pengalaman mengasuh anak membawa saya pada kesadaran lain: orangtua pun sejatinya murid. Kita belajar ulang tentang kesabaran ketika anak berulah. Kita belajar kembali arti kejujuran ketika mereka bertanya hal-hal polos tapi menohok. Kita belajar menundukkan ego ketika pilihan mereka berbeda dengan rencana kita.
Dengan kata lain, proses mengasuh anak adalah sekolah kehidupan bagi orangtua. Anak adalah cermin—menyingkap kelemahan sekaligus mengasah kebijaksanaan kita.
Namun, banyak orangtua lupa bahwa mereka pun masih belajar. Mereka ingin anaknya cepat matang, sementara dirinya sendiri masih bergulat dengan emosi, ambisi, dan trauma yang belum selesai. Sikap merasa paling tahu sering kali justru menjauhkan kita dari anak. Saat suara anak tak lagi didengar, jarak emosional pun terbentuk.
Bahaya Membandingkan
Kita hidup di era serba cepat, serba pamer, dan serba banding. Media sosial memperparah keadaan: nilai rapor, medali lomba, hingga jumlah followers sering dijadikan tolok ukur keberhasilan. Tak jarang, foto anak sedang menerima piala lebih cepat tersebar daripada anak itu sendiri memahami arti dari sebuah kemenangan.
Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang ekspektasi yang kerap melampaui kapasitas dirinya. Perasaan tidak cukup, tidak sehebat teman, bisa muncul sejak dini. Padahal, pendidikan sejatinya bukan lomba siapa tercepat atau terhebat. Yang lebih penting adalah memastikan anak tumbuh sehat, bahagia, dan berkarakter.
Prestasi akademik memang penting, tetapi itu bukan satu-satunya jalan menuju kehidupan bermakna. Banyak orang sukses justru lahir dari proses jatuh bangun, dari keberanian mengambil jalan berbeda, bukan dari sekadar memenuhi standar nilai rapor.
Belajar dari Paulo Freire
Dalam Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire menolak konsep pendidikan gaya “bank” di mana guru (atau orangtua) seolah hanya “menyetorkan” pengetahuan ke kepala anak. Bagi Freire, pendidikan sejati adalah praksis kebebasan, di mana manusia belajar membaca realitas, lalu berdaya mengubahnya.
Kutipannya yang masyhur berbunyi: “Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system, or it becomes the practice of freedom.”
Diterjemahkan bebas: pendidikan bisa jadi alat penjinakan, atau sebaliknya, praktik kebebasan.
Relevansinya jelas: mendidik anak bukan sekadar memindahkan pengetahuan atau mewariskan ambisi, melainkan membebaskan mereka untuk mengenali dirinya, memahami lingkungannya, lalu berani menentukan jalannya sendiri.
Jika orangtua masih bersikeras menjadikan anak replika dirinya, maka pendidikan justru kehilangan ruhnya. Anak tidak sedang dimerdekakan, melainkan sedang dijajah dengan cara halus.
Maka disini saya perlu merujuk Freire untuk mendefinisikan ‘merdeka’, dan membuat pagar bahwa kemerdekaan yang dimaksud adalah: tidak ada yang menindas dan tidak ada yang tertindas.
Saya tidak sedang mendengungkan Freire sebagai gaya parenting. Hanya mencuplik kacamata Freire tentang kemerdekaan. Bahwa dalam mengasuh anak pun ternyata kita orang dewasa yang merasa tahu apa yang terbaik untuk anaknya tanpa disadari sangat bisa berperan menjadi ‘penindas’ bagi anak-anak kita.
Merdeka dalam Cinta
Tentu melihat potensi anak sendiri tampaknya tak begitu sulit. Terutama jika kacamata kita adalah DNA. Dengan menyadari bahwa setengah DNA anak adalah berasal dari diri kita, maka kemungkinan besar minatnya tak jauh-jauh dari salah satu orangtuanya. Saya pun kerap mengintip coretan anak saya, dan berharap kelak ia mampu menggambar lebih baik dari saya. Namun kacamata DNA ini seringkali terkaburkan dengan kacamata lain, yaitu obsesi.
Orangtua sangat mungkin terjebak dengan menganggap obsesi anak dan obsesinya sendiri takjauh beda. Tentu hal ini akan menjerumuskan pada pola didik ‘obsesi terpendam’, dimana orangtua menuntut anaknya menjadi sesuatu yang ‘tak sampai’ ia capai dahulu.
Baru ketika anak enggan sekolah, ketika tugas sekolah mogok di jalan, dan ketika anak memunculkan gejala ketertindasan lain ke permukaan, orangtua resah. Merasa telah melakukan segala hal dan tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Padahal sang anak hanya sedang mengirim sinyal kuat yang bunyinya: Pak, Buk, aku tertindas!
Memerdekakan anak tidak berarti melepaskan tanpa arah. Kebebasan tanpa batas hanya melahirkan kebingungan.
Sebaliknya, memerdekakan anak berarti mencintai tanpa memiliki.
Orangtua hadir sebagai pagar: cukup kokoh untuk melindungi, sekaligus cukup longgar untuk memberi ruang tumbuh. Dalam kerangka ini, tugas kita bukan mencetak anak sesuai desain, melainkan mendampingi agar mereka menemukan jalannya sendiri.
Kita mengarahkan, bukan mendikte. Kita membimbing, bukan mengendalikan. Kita mencintai, bukan menguasai.
Praktik Kecil Sehari-hari
Bagaimana praktik memerdekakan anak dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara sederhana:
Mendengar lebih banyak. Tahan keinginan untuk buru-buru menasihati. Dengarkan dulu cerita anak, sekecil apa pun itu.
Memberi pilihan. Biarkan anak memilih baju yang ingin ia kenakan, atau buku cerita yang ingin ia baca. Dari hal kecil inilah otonomi terbentuk.
Menghargai proses, bukan hanya hasil. Alih-alih menanyakan “dapat nilai berapa?”, lebih baik bertanya “apa yang kamu pelajari hari ini?”.
Mengakui kesalahan orangtua. Tak ada yang salah dengan berkata, “Ayah tadi keliru marah-marah.”
Justru dari situ anak belajar bahwa orang dewasa pun bisa salah, dan kesalahan bisa diperbaiki.
Praktik sederhana ini membantu anak tumbuh sebagai pribadi merdeka, sekaligus melatih orangtua untuk lebih rendah hati.
Ngudar Rasa
Kadang, saat malam menjelang, saya duduk menatap wajah anak yang terlelap. Ada damai yang sulit diungkapkan. Ada pula rasa gentar: apakah saya sudah cukup bijak mendampingi pertumbuhannya? Atau jangan-jangan saya terlalu sibuk mengukur dengan standar saya sendiri?
Di titik itulah saya belajar kembali: anak bukan cermin ego orangtua, melainkan titipan yang harus dijaga agar kelak bisa menemukan jalannya sendiri. Tugas saya hanyalah menemani, bukan menggiring.
Dan mungkin, memang di situlah seni terbesar menjadi orangtua: menahan diri untuk tidak selalu benar, dan belajar ikhlas bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang membebaskan.
Maka disinilah titik renungnya: bahwa memerdekakan anak itu sulit luar biasa. Antara ‘sayang’ atau ‘tidakpercaya’ menjadi beda tipis. Keputusan mengirim anak mengikuti les, misalnya, bisa saja bentuk rasa sayang kita.
Namun bisa jadi itu bentuk rasa tidak percaya bahwa anak bisa belajar sendiri hal-hal yang ia sukai. Untuk itu alangkah baiknya jika orangtua selalu ingat “bahwa anak adalah mahaguru bagi dirinya, dan sumber ilmu bagi teman-temannya” ungkapan yang dulu sering dilontarkan almarhum Romo YB. Mangun Widjaya, dan hakekatnya: kita tidak pernah benar-benar memerdekakan seekor burung jika ekornya masih kita genggam.
Mari kembali belajar memerdekakan anak dengan benar.